by Dadang Kadarusman
Dimasa kecil, ketika pelajaran kesenian tiba, Ibu guru meminta setiap anak untuk bernyanyi didepan kelas. Kita bersembunyi dikolong meja dengan debaran jantung teramat kencang, berusaha menghindari giliran. Kita merasa malu. Ketika beranjak remaja, Ayah dan Ibu bilang:”Kamu ini bikin malu keluarga saja!”. Saat memasuki usia dewasa muda, kita duduk dibangku kuliah berhadapan dengan dosen yang sangat cerdas. Dia tahu kita tidak mengerti rumus-rumus abstrak yang dilukisnya dipapan tulis. Beliau bertanya:”Siapa yang belum mengerti?” Kita terdiam. Membisu. Malu ketahuan teman kalau kita ini bodoh. Dan. Ketika sudah benar-benar dewasa, kita duduk di kursi hotel untuk sebuah pelatihan dari seorang trainer hebat. Ketika trainer itu bertanya:”Bapak, Ibu, silakan jika ada yang ingin ditanyakan…” Kita terdiam. Malu. Masak, pangkat manajer kok mengajukan pertanyaan sedungu itu. Kemudian kepada kita dikatakan; ”Buanglah jauh-jauh rasa malu. Karena itu akan menghambat keberhasilanmu!” Benarkah demikian?
Seorang salih yang dicintai umatnya mengatakan:”Rasa malu itu adalah bagian dari Iman.” Dengan kata lain, keimanan seseorang tidaklah sempurna seandainya orang yang mengaku beriman itu tidak memiliki rasa malu. Sekarang pilihannya ada pada diri anda; apakah anda ingin menjadi orang berhasil dalam karir, atau menjadi orang yang beriman dengan keimanan yang utuh? Jika anda ingin sukses berkarir, buang rasa malu dari dalam diri anda! Jika anda ingin menjadi orang beriman, pupuk dan hidupkan rasa malu dalam diri anda! Gampang, kan? Tetapi, benarkah kita harus demikian? Tidakkah keimanan dan kesuksesan bisa seiring sejalan?
Kita seringkali mencampakkan ajaran-ajaran normatif seperti itu. Mungkin karena terlalu dipengarui oleh hawa hedonisme, dimana materi menjadi tolak ukur paling dominan. Hidup kita, dinilai dari jenis mobil yang dikendarai. Kemegahan rumah yang kita huni. Label pakaian yang kita kenakan. Gelar yang menempel pada nama kita. Dan jabatan atau pangkat yang melekat dipundak kita. Ajaibnya, kita meyakini bahwa kalau kita malu, tidak mungkin semuanya itu bisa kita raih. Oleh karena itu, mengapa kita mesti malu melakukan ini dan itu. Mengapa kita mesti malu melabrak sana sini. Menyikut kanan dan kiri. Mengambil. Merenggut. Meraup. Apa saja. Supaya dalam sekejap, kita bisa mendapatkan segala-galanya. Mengapa mesti malu?
”Buanglah jauh-jauh rasa malu. Karena itu akan menghambat keberhasilanmu!” Rasa malu seperti apa yang mesti kita buang jauh-jauh? Malu bertanya sesat dijalan, katanya. Jadi, mungkin harus membuang rasa malu itu. Sebab, kalau malu bertanya kita akan tersesat. Bisa iya. Bisa tidak. Anda, jika sudah memiliki fasilitas GPRS; tidak usah lagi bertanya. Tidak akan pernah tersesat lagi, kok. Anda, jika sudah punya asisten pribadi yang hebat; mengapa masih harus bertanya? Cukup anda katakan kepadanya: ”Aku tidak mau tahu bagaimana caranya, tapi kamu harus kerjakan ini untukku!”. Besok pagi hasilnya sudah tertata rapi diatas meja kerja anda yang mewah. Masih haruskah anda bertanya? Jika anda malu tampil didepan orang banyak untuk sebuah pidato yang bermutu, mengapa pusing. Minta saja pegawai anda mengadakan kontes untuk mencari orang yang mirip dengan anda; dan suruh dia bicara didepan publik untuk anda. Masihkah anda membutuhkan rasa malu?
”Rasa malu itu adalah bagian dari Iman.” Ngomong apa sih sang Nabi ini? Please, deh. Jangan kaitkan soal rasa malu dengan keimanan! Baiklah, kita hentikan semua omong kosong ini sampai disini. Tapi sebelum itu, coba kita perhatikan beberapa hal berikut ini. Seorang beriman akan merasa malu jika dia tidak bisa mempersembahkan hasil pekerjaan yang baik untuk perusahaan yang menggajinya. Seorang beriman akan malu jika kemampuan dirinya lebih rendah dibandingkan rekan sejawat yang bekerja dalam tanggungjawab yang sama, digaji sama, diberi fasilitas sama, dan diperlakukan sama. Dia malu jika membiarkan dirinya terus menerus ketinggalan. Dan dia malu, jika meminta kenaikan gaji padahal dia tahu; dia belum bekerja maksimal untuk perusahaan. Seorang yang beriman, malu jika menyalahgunakan fasilitas dan kesempatan yang dia dapatkan. Seorang yang beriman malu, jika menggunakan kewenangan untuk memeras para pemasok barang. Dan seorang yang beriman malu, jika harus mengambil sesuatu yang bukan haknya.
Oleh dasar rasa malu itu; seorang yang beriman, dalam bekerja pasti akan mempersembahkan prestasi puncaknya. Dan oleh dasar rasa malu itu; seorang beriman akan sadar bahwa bertanya merupakan tugas dirinya yang belum mengetahui suatu hal. Malu dia, jika nanti setelah mengikuti pelatihan, pengetahuan dan kemampuannya sama sekali tidak ada penambahan. Jadi pastilah dia akan bersungguh-sungguh dalam melakukan apapun yang menjadi tanggungjawabnya. Seorang atasan yang beriman malu jika semua kesalahan ditimpakan kepada anak buahnya. Apa fungsi atasan jika demikian? Seorang anak buah yang beriman, malu jika keberadaannya sama sekali tidak menyebabkan segala sesuatunya lebih mudah bagi sang atasan. Apa guna seorang bawahan jika demikian? Seorang kolega yang beriman, malu jika kehadirannya sama sekali tidak menyebabkan teman-temannya dalam team terbantu. Dan seorang pegawai yang beriman, malu dia; kalau sampai tugas-tugasnya terbengkalai. Seorang karyawan yang beriman akan malu jika dia masuk ke kantor selalu terlambat, dan terbiasa pulang cepat-cepat. Dan karyawan yang beriman akan malu jika menghabiskan waktu berjam-jam untuk makan siang dengan desert berupa rumpi yang tidak karuan. Dia akan malu juga, jika setelah menyia-nyiakan jam kerja itu tetap tinggal dikantor sampai larut malam agar perusahaan membayar upah lembur. Dan orang yang beriman; akan malu jika menyia-nyiakan kesempatan untuk dipromosikan. Sehingga dia akan berusaha sekuat tenaga, agar memiliki kualitas yang jauuuuuuuuuuh lebih baik dari teman-temannya yang lain. Agar nanti, jika ada lowongan jabatan yang lebih tinggi – management tidak ragu memilihnya untuk dipromosikan. Karena, ”Rasa malu itu adalah bagian dari Iman.”
Kita bisa menjadi orang beriman yang sukses, bukan? Tentu saja bisa. Sebab ternyata, sang Nabi merancang konsep rasa malu dalam iman itu untuk memastikan bahwa umatnya benar-benar meraih kesuksesan dalam hidup, dan dalam mati. Dalam hidup dengan rasa malu itu, kita dibimbing untuk menjadi pribadi-pribadi yang unggul. Dan bisa diandalkan. Layak untuk diberi tanggungjawab besar. Patut untuk menjadi panutan. Dan pantas dijadikan tempat dimana orang-orang lainnya mendapatkan pencerahan. Dalam mati dengan rasa malu, kita meninggalkan jejak-jejak keterpujian. Untuk dicatatkan oleh malaikat sebagai kebajikan. Untuk menjadi landasan, mengapa dia layak mendapatkan imbalan dari Tuhan. Dan untuk menjadikannya modal agar pantas mendapat tempat yang terpuji disisi-Nya. Kadang kita mengatakan ’telah berpulang ke rahmatullah’. Mana mungkin kita benar-benar kembali kepada rahmat Allah, jika ketika mati, kita tak memiliki rasa malu? Mungkin kita mengatakan ’telah berpulang kerumah bapa di surga’. Mana mungkin pintu rumah Allah akan dibukakan untuk kita; sendainya kita tidak memiliki rasa malu? Bahkan, untuk memasuki rumah tetangga saja kita harus memiliki rasa malu itu. Bukankah tidak ada orang yang senang dikunjungi oleh jenis manusia yang tidak tahu malu? Jadi, bagaimana kita bisa masuk surga kalau pintunya tidak dibuka pemiliknya? Karena sang pemilik surga hanya akan membukakan pintu itu bagi mereka yang benar-benar beriman. Sedangkan kata Pak Muhammad: ”Rasa malu itu adalah bagian dari Iman.” Dan kalau tidak kesurga, kemana lagi kita akan kembali pulang?
Catatan kaki:
Jika dirawat dan dimanfaatkan dengan tepat; rasa malu akan membantu kita untuk tumbuh menjadi pribadi yang berhasil meraih keagungan didalam kedua kehidupan
Sabtu, 15 Desember 2007
Benarkah Kita Harus Membuang Rasa Malu
Label:
inspirasi
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
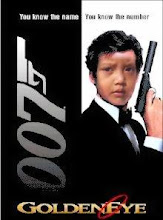

Tidak ada komentar:
Posting Komentar